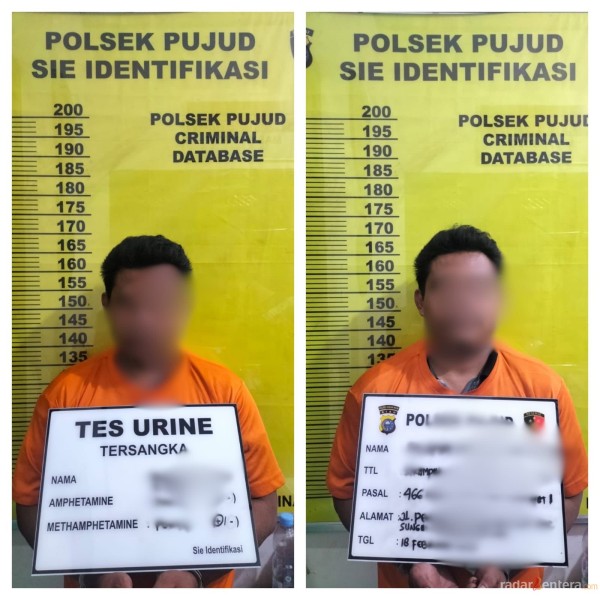Alarm tua itu kembali berbunyi pukul tiga dini hari.
Fulan terbangun dengan mata basah, bukan karena mimpi, tapi karena kenyataan yang selalu sama setiap Ramadhan datang.
Ia duduk di tepi ranjang, menatap kursi kosong di sudut kamar.
- Baca Juga Tangis di Sepertiga Malam
Dulu, di kursi itu, ayahnya biasa duduk sambil mengenakan peci, menunggu Fulan bangun sahur.
Dulu, dari dapur, suara ibu selalu terdengar lembut,
“Fulan, sahurnya jangan lupa ya, Nak…”
Sekarang, tak ada siapa-siapa.
Hanya sunyi.
Dan rindu yang tidak pernah selesai.
- Baca Juga Senja yang Tak Pernah Sama
Fulan berjalan ke dapur. Ia menanak nasi sendirian, tangannya gemetar. Saat menuangkan air ke panci, ia teringat ibu yang dulu selalu berkata, “Kalau masak, niatkan ibadah.”
Air matanya jatuh ke lantai.
Ia makan sahur sendirian. Tidak ada yang bertanya apakah ia sudah kenyang, tidak ada yang mengingatkan untuk minum.
Di sela suapan, Fulan berhenti.
“Ya Allah… ayah… ibu… lihat aku ya. Aku puasa lagi…”
Tapi tidak ada jawaban.
Hanya jam dinding yang terus berdetak.
Siang hari terasa sangat panjang. Perut lapar, kepala pusing, dan hati lebih lapar dari segalanya. Di sekolah, teman-temannya mengeluh soal makanan buka puasa.
Fulan diam.
Baginya, makanan bukan hal yang paling berat.
Yang paling berat adalah tidak ada yang menunggu saat ia pulang.
Menjelang maghrib, Fulan berjalan pelan melewati rumah-rumah yang lampunya mulai menyala. Dari jendela, ia melihat keluarga-keluarga berkumpul. Ayah, ibu, anak-anak. Tertawa. Berdoa bersama.
Fulan berhenti di depan rumahnya sendiri.
Pintu tertutup.
Gelap.
Sepi.
Azan maghrib terdengar dari kejauhan.
Fulan duduk di lantai rumahnya, membuka puasa hanya dengan air putih.
Sambil meneguk air, dadanya terasa sesak.
“Ayah… Ibu… Fulan kuat kok… walaupun sendirian…”
Air mata jatuh ke gelasnya.
Malam itu, Fulan shalat tarawih sendirian. Seusai shalat, ia menengadahkan tangan lama sekali.
“Ya Allah… kalau ayah dan ibu masih hidup, aku ingin mereka bangga padaku.
Kalau mereka sudah tiada, tolong sampaikan…
bahwa anak mereka tidak meninggalkan puasa,
tidak meninggalkan-Mu.”
Tangisnya pecah.
Di bulan Ramadhan itu, Fulan belajar bahwa menjadi yatim piatu bukan hanya tentang kehilangan orang tua, tapi tentang menyimpan rindu setiap hari, dan menahannya demi taat kepada Allah.
Dan setiap puasanya,
bukan hanya menahan lapar,
tetapi juga menahan perih yang tidak pernah sembuh.