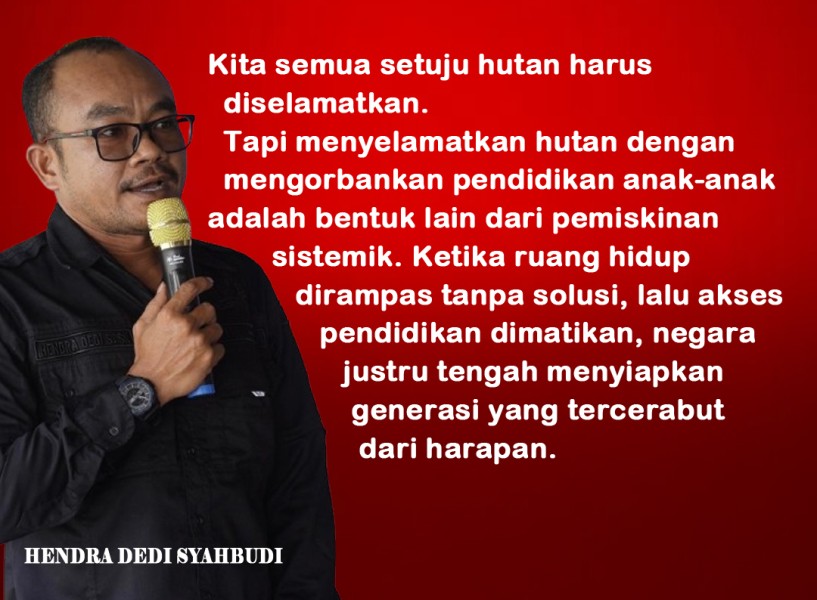Oleh: Hendra Dedi Syahbudi
Sebuah potret menyayat hati kembali membangunkan nurani kita, puluhan anak-anak SD duduk di atas terpal plastik di bawah pohon sawit, di tengah rimbunnya kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Pelalawan, Riau. Mereka berseragam merah-putih, tapi tak punya kelas. Mereka murid, tapi tak punya sekolah. Mereka generasi penerus, tapi sedang ditinggal oleh kebijakan negara yang gagal menyiapkan ruang tumbuh.
Ini bukan cerita fiksi. Ini nyata. Ini Indonesia.
Konservasi Tanpa Konsekuensi
Berangkat dari kebijakan pelarangan penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan TNTN oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), ratusan anak, termasuk 58 murid SD di Dusun Toro Jaya, tidak dapat mengakses pendidikan formal. Sekolah mereka dianggap ilegal karena berada di kawasan konservasi. Para orang tua pun diminta mendaftarkan anak ke sekolah induk yang berjarak dua jam dari pemukiman. Dua jam jalan kaki, bagi anak usia tujuh tahun, di tengah hutan?
Kita patut bertanya: adakah negara hadir dalam kebijakan ini?
Tentu, konservasi penting. Kita semua setuju hutan harus diselamatkan. Tapi menyelamatkan hutan dengan mengorbankan pendidikan anak-anak adalah bentuk lain dari pemiskinan sistemik. Ketika ruang hidup dirampas tanpa solusi, lalu akses pendidikan dimatikan, negara justru tengah menyiapkan generasi yang tercerabut dari harapan.
Pendidikan Adalah Hak, Bukan Pilihan
Konstitusi kita tegas: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lebih dari sekadar hak, pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan keterbelakangan. Namun, apa jadinya jika anak-anak harus belajar di bawah pohon sawit karena negara terlalu sibuk menjaga batang kayu, tetapi lupa menjaga isi kepala anak bangsanya?
Pemerintah berdalih proses relokasi sedang disiapkan, bahwa ini hanya sementara. Tapi keterlambatan penanganan bukan alasan. Yang salah dari awal adalah ketidaksiapan infrastruktur pengganti sebelum kebijakan penutupan diterapkan. Negara semestinya tidak mencabut sekolah sebelum membangun harapan baru.
Negara Tidak Boleh Gagal di Sini
Anak-anak di bawah pohon sawit adalah sinyal kegagalan kolektif. Kegagalan merancang transisi yang manusiawi. Kegagalan memahami bahwa relokasi bukan hanya soal tanah, tapi juga tentang identitas, budaya, dan hak hidup. Negara hadir bukan untuk melarang, melainkan untuk memfasilitasi. Negara tidak boleh hanya datang sebagai penjaga hutan, tetapi juga sebagai pengasuh masa depan anak-anak.
Pendidikan dan konservasi seharusnya berjalan beriringan. Hutan bisa diselamatkan tanpa harus mengorbankan anak-anak. Yang dibutuhkan adalah pendekatan kolaboratif: kelas darurat di luar kawasan, transportasi ke sekolah induk, guru relawan, dan tentu, ketegasan anggaran.
Saya percaya, anak-anak ini masih punya masa depan. Tapi masa depan mereka sangat tergantung pada seberapa cepat negara membuka mata dan merespons krisis ini dengan hati dan logika. Jangan biarkan mereka tumbuh dengan ingatan bahwa sekolah pertama mereka bukanlah ruang kelas, tapi kebun sawit. Bahwa mereka belajar bukan di bawah atap, tapi di bawah langit yang terlalu sering diabaikan.
Negara tidak boleh gagal lagi.
Penulis adalah Pemimpin Redaksi RadarLentera.com